|
Teori perintah Ilahi Teori perintah Ilahi (juga dikenal sebagai volunterisme teologis)[1][2] adalah sebuah teori meta-etika yang menyatakan bahwa status suatu tindakan dianggap sebagai baik secara moral apabila tindakan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Teori ini menyatakan bahwa apa yang disebut bermoral ditentukan oleh perintah Tuhan dan seseorang yang bermoral harus mengikuti perintah Tuhan. Pengikut agama monoteistik dan politeistik pada zaman dahulu hingga sekarang sering menerima pentingnya perintah Tuhan dalam membangun moralitas. Berbagai varian dari teori perintah ilahi disampaikan secara historis oleh tokoh-tokoh terkemuka termasuk Saint Augustine, Duns Scotus, William dari Ockham dan Søren Kierkegaard. Mereka menyampaikan berbagai variasi teori perintah ilahi, dan yang baru-baru ini adalah Robert Merrihew Adams mengusulkan "teori perintah ilahi yang dimodifikasi" berdasarkan kemahakuasaan Tuhan yang di mana moralitas dikaitkan dengan konsepsi manusia tentang benar dan salah. Paul Copan mendukung teori ini dari sudut pandang Kristen, dan teori motivasi ilahi Linda Trinkaus Zagzebski juga mengusulkan bahwa yang sesungguhnya ialah motivasi Tuhan yang menjadi sumber moralitas, bukan perintah Tuhan. Beberapa tantangan terhadap teori perintah ilahi telah diajukan. Filsuf William Wainwright yang menantang secara semantik berargumen bahwa kata diperintahkan oleh Tuhan dengan wajib secara moral memiliki arti yang tidak sama, yang di mana ia meyakini bahwa jika kedua hal itu disamakan, maka akan mempersulit pendefinisian akan kewajiban. Dia juga berpendapat bahwa karena pengetahuan tentang Tuhan diperlukan untuk moralitas oleh teori perintah ilahi, maka ateis dan agnostik dianggap tidak bermoral dalam teori ini. William melihat hal ini sebagai kelemahan dari teori perintah ilahi. Yang lainnya juga telah menantang teori tersebut berdasarkan logika modal dengan berargumen bahwa, bahkan jika perintah Tuhan dan moralitas berkorelasi di dunia ini, mereka mungkin tidak melakukannya di dunia lain yang mungkin. Selain itu, dalam dilema Euthyphro yang pertama kali dikemukakan oleh Plato (dalam konteks agama Yunani yang sifatnya politeistik), menghadirkan dilema yang akan mengakibatkan kesewenang-wenangan moral dari moralitas itu sendiri, atau mengakibatkan tidak relevannya Tuhan dengan moralitas. Teori perintah ilahi juga banyak dikritik karena ketidaksesuaiannya dengan sifat kemahakuasaan Tuhan, otonomi moral dan pluralisme agama, meskipun berbagai sarjana juga telah berusaha untuk mempertahankan teori tersebut dari tantangan-tantangan yang telah diajukan. Bentuk umumPara filsuf termasuk William dari Ockham ( ca 1287 – 1347), St Augustine (354-430), Duns Scotus ( ca 1265 – 1308), dan John Calvin (1509-1564) menyampaikan berbagai bentuk dari teori perintah ilahi. Teori ini umumnya mengajarkan bahwa kebenaran moral tidak dapat berdiri sendiri tanpa Tuhan serta perintah Tuhanlah yang menentukan moralitas itu sendiri. Versi teori yang lebih kuat menegaskan bahwa perintah Tuhan adalah satu-satunya alasan bahwa tindakan yang baik adalah moral, sementara variasi yang lebih lemah menjadikan perintah Tuhan sebagai komponen penting dalam alasan yang lebih besar.[3] Teori ini menyatakan bahwa tindakan yang baik secara moral dianggap baik dikarenakan perintah yang dikeluarkan oleh Tuhan, dan banyak penganut agama menganut beberapa varian teori perintah ilahi tersebut.[4] Karena premis-premis tersebut, penganut teori ini percaya bahwa kewajiban moral adalah ketaatan terhadap perintah Tuhan; apa yang benar secara moral adalah apa yang diinginkan Tuhan dan apa yang buruk secara moral adalah hal yang dilarang oleh Tuhan.[5] Teori perintah ilahi dalam etika mengandung beragam corak dari berbagai agama kontemporer seperti Yudaisme, Islam, Kepercayaan Baháʼí, dan Kristen, serta terdapat dalam banyak agama politeistik.[6] Di Athena kuno, warga umumnya berpendapat bahwa kebenaran moral terkait langsung dengan perintah ilahi, dan kesalehan agama dikatakan setara dengan orang yang baik secara moralitas.[7] Meskipun Kekristenan tidak memerlukan teori perintah ilahi, orang biasanya mengaitkan antara moralitas dengan teori tersebut. Teori perintah ilahi dapat menjadi teori yang masuk akal bagi orang Kristen karena konsepsi tradisional tentang Tuhan sebagai pencipta alam semesta sejajar dengan gagasan bahwa Dia juga menciptakan kebenaran moral. Teori ini didukung oleh pandangan Kristen bahwa Tuhan itu mahakuasa dan ini juga menyiratkan bahwa Tuhan menciptakan kebenaran moral karena kemahakuasaan-Nya, daripada kebenaran moral yang ada secara independen dari diri Tuhan, yang tampaknya tidak sesuai dengan kemahakuasaan-Nya.[3] Agustinus Santo Agustinus menawarkan versi teori perintah ilahi yang dimulai dengan menetapkan etika sebagai pengejaran kebaikan tertinggi, yang dapat memberikan kebahagiaan manusia. Dia berargumentasi bahwa untuk mencapai kebahagiaan ini, manusia wajib mencintai objek yang layak untuk dicintai oleh manusia dengan cara yang benar. Konsep ini menuntut manusia untuk mencintai Tuhan, yang kemudian dengan cinta kepada Tuhan tersebut dapat menuntun mereka untuk mencintai dengan benar apa yang layak untuk dicintai. Etika Agustinus mengajukan bahwa tindakan mencintai Tuhan memungkinkan manusia untuk mengarahkan cinta mereka dengan benar, yang kemudian dengan cinta yang benar itu dapat mengarah pada kebahagiaan dan pemenuhan manusia.[5] Agustinus mendukung pendapat Plato bahwa jiwa yang teratur dengan baik adalah konsekuensi yang diinginkan dari moralitas. Namun, tidak seperti Plato, dia percaya bahwa mencapai jiwa yang teratur dengan baik tersebut memiliki tujuan yang lebih tinggi lagi, yaitu hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Pemikirannya tentang moralitas dengan demikian termasuk ke dalam kategori heteronom, karena ia percaya pada penghormatan kepada otoritas yang lebih tinggi (Tuhan), daripada bertindak secara otonom.[8] John Duns Scotus Filsuf skolastik John Duns Scotus berpendapat bahwa satu-satunya kewajiban moral yang tidak dapat dikehendaki untuk dicabut oleh Tuhan dari manusia adalah mencintai diri-Nya, karena Tuhan, secara definisi, adalah hal yang paling dicintai.[9] Scotus berpendapat bahwa hukum kodrat, dalam penafsiran yang paling sempit, hanya mengandung apa yang secara analitis terbukti benar dan bahwa Tuhan tidak dapat membuat pernyataan-pernyataan tersebut salah. Hal ini berarti bahwa perintah yang didasarkan pada hukum kodrat tidak bergantung pada kehendak Tuhan, dan dengan demikian membentuk tiga perintah pertama dari Sepuluh Perintah Tuhan. Tujuh perintah terakhir dari Sepuluh Perintah Tuhan tidak termasuk ke dalam hukum kodrat dalam arti yang sesungguhnya.[10] Sehingga kewajiban kita yang ditujukan kepada Tuhan jelas dengan sendirinya, benar menurut definisi, dan tidak dapat diubah bahkan oleh Tuhan itu sendiri, sedangkan tugas kita yang diwajibkan kepada orang lain (ditemukan pada lauh kedua) secara bebas dikehendaki oleh Tuhan dan berada dalam ranah kekuasaan-Nya untuk mencabut dan menggantinya (meskipun, ketiga perintah lainnya seperti menghormati hari Sabat dan menyucikannya, memiliki sedikit pengaruh dari hukum kodrat dan kehendak Tuhan, karena kita secara absolut berkewajiban untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak ada kewajiban dalam hukum kodrat untuk melakukannya pada hari tertentu). Scotus mencatat bahwa bagaimanapun tujuh perintah terakhir tersebut
Scotus membenarkan posisi ini dengan memberi contoh masyarakat yang tenteram. Dia mencatat bahwa kepemilikan properti pribadi tidak diperlukan untuk membentuk masyarakat yang tenteram, akan tetapi untuk "mereka yang berkarakter lemah" akan lebih mudah dibuat aman dengan kepemilikan properti pribadi tersebut daripada tanpanya. Oleh sebab itu, tujuh perintah terakhir memang termasuk ke dalam hukum kodrat, tetapi tidak dalam arti yang paling ketat, karena mereka termasuk ke dalam hukum kodrat secara terus terang daripada menurut definisi. Thomas Aquinas
Sementara Aquinas, sebagai ahli teori hukum kodrat, pada umumnya dianggap mempunyai pandangan bahwa moralitas tidak dikehendaki oleh Tuhan.[15] Kelly James Clark dan Anne Poortenga telah mengusulkan pembelaan teori perintah ilahi berdasarkan model teori moral Aquinas. Aquinas mengusulkan teori hukum kodrat yang menegaskan bahwa sesuatu itu dapat disebut bermoral apabila bekerja untuk tujuan keberadaan manusia, sehingga sifat manusia dapat menentukan apa itu moral. Clark dan Poortenga berargumen bahwa Tuhan menciptakan sifat manusia dan dengan demikian hal itu dapat membentuk moralitas tertentu. Sehingga Tuhan tidak dapat seenaknya mengubah apa yang benar atau salah bagi manusia.[5] Immanuel KantBeberapa tokoh seperti ahli etika RM Hare menghapus Etika deontologis Immanuel Kant sebagai tesis yang menolak keberadaan teori perintah ilahi. Pandangan Kant bahwa moralitas harus didasarkan pada imperatif kategoris yaitu kewajiban terhadap hukum moral daripada bertindak untuk motif tertentu dianggap tidak sesuai dengan teori perintah ilahi. Filsuf dan teolog John E. Hare telah mencatat bahwa beberapa filsuf menganggap teori perintah ilahi sebagai contoh kehendak heteronom Kant. Sehingga menurut Kant, motif selain hukum moral dapat dianggap sebagai bagian dari hukum non-moral.[16] Filsuf Amerika Lewis White Beck berpendapat bahwa argumentasi Kant sebagai sanggahan terhadap teori moralitas yang bergantung pada kewenangan Tuhan.[17] John E. Hare menentang pandangan tersebut dengan alasan bahwa etika Kantian perlu dibaca sesuai dengan teori perintah ilahi.[16] Robert Adams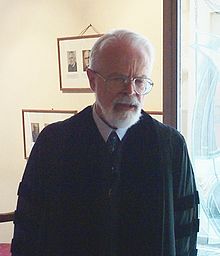 Seorang filsuf Amerika Robert Merrihew Adams mengajukan apa yang ia sebut sebagai "teori perintah ilahi yang dimodifikasi".[18] Adams menyampaikan bentuk dasar teorinya dengan menyatakan bahwa terdapat dua pernyataan adalah ekuivalen:
Dia mengusulkan bahwa perintah Tuhan mendahului kebenaran moral dan perlu dijelaskan dalam ketentuan kebenaran moral, bukan kebenaran moral yang mendahului perintah Tuhan. Adams menulis bahwa teorinya merupakan sebuah upaya untuk mendefinisikan apa yang disebut sebagai "salah" secara etis dan menyetujui bahwa teori tersebut hanya berguna bagi mereka yang berada dalam konteks Yahudi-Kristen. Dalam menghadapi kritik bahwa tindakan yang tampaknya tidak bermoral akan menjadi kewajiban jika Tuhan memerintahkannya, ia mengusulkan bahwa Tuhan tidak memerintahkan kezaliman karena kehendaknya sendiri. Adams tidak mengusulkan bahwa secara logis tidak mungkin bagi Tuhan untuk memerintahkan kezaliman, melainkan Adams mengusulkan bahwa tindakan zalim tersebut tidak terpikirkan bagi Tuhan untuk melakukan hal tersebut karena sifat-sifat-Nya. Adams menekankan pentingnya iman kepada Tuhan, khususnya iman akan kebaikan Tuhan, serta keberadaan-Nya.[20] Adams mengusulkan bahwa suatu tindakan secara moral salah jika dan hanya jika itu melanggar perintah Tuhan yang pengasih. Adams berargumen bahwa dalam hal ini, semua perintah Tuhan tidak harus dipatuhi dan juga teori tentang kesalahan etis akan jatuh. Dia mengusulkan bahwa moralitas perintah ilahi mengasumsikan konsep manusia tentang benar dan salah dapat dipenuhi oleh perintah Tuhan dan teori itu hanya dapat diterapkan jika berada di dalam masalah ini.[21] Teori Adams mencoba untuk melawan tantangan bahwa moralitas dari teori perintah ilahi mungkin sewenang-wenang, karena perintah moral tidak hanya didasarkan pada perintah Tuhan, tetapi didasarkan pada kemahakuasaan-Nya juga. Adams mencoba untuk menantang klaim bahwa standar moralitas eksternal mencegah Tuhan berdaulat dengan menjadikan Tuhan sumber moralitas beserta sifat-sifat-Nya sebagai hukum moral.[5] Adams mengusulkan bahwa dalam banyak konteks Yudeo-Kristen, istilah "salah" digunakan ketika hal itu bertentangan dengan perintah Tuhan. Dalam konteks etika, ia percaya bahwa "salah" memerlukan sikap emosional terhadap suatu tindakan dan penggunaan kata salah dalam kedua konteks sebelumnya biasanya berhubungan.[22] Adams menyarankan bahwa konsep moralitas orang beriman didasarkan pada keyakinan agama mereka dan bahwa benar dan salah terikat pada keyakinan mereka pada Tuhan. Usulan ini bekerja karena Tuhan selalu memerintahkan apa yang orang beriman terima sebagai kebenaran. Jika Tuhan memerintahkan apa yang dianggap salah oleh orang yang beriman, orang beriman tidak akan mengatakan itu benar atau salah untuk tidak menaatinya, melainkan karena hal itu akan membuat konsep moralitas mereka akan runtuh.[23] Michael Austin menulis bahwa implikasi dari teori perintah ilahi yang dimodifikasi ini adalah Tuhan tidak dapat memerintahkan kezaliman karena kehendaknya sendiri. Hal itu bisa dikatakan tidak selaras dengan sifat kemahakuasaan Tuhan. Thomas Aquinas berargumen bahwa kemahakuasaan Tuhan harus dipahami sebagai kemampuan untuk melakukan segala sesuatu yang mungkin. Thomas berusaha untuk menyanggah gagasan bahwa ketidakmampuan Tuhan untuk melakukan tindakan yang tidak logis menantang sifat kemahakuasaan-Nya. Austin berpandangan bahwa memerintahkan kezaliman karena kehendak Tuhan sendiri bukanlah hal yang tidak logis, sehingga tidak tercakup dalam pembelaan Aquinas, meskipun Aquinas berpendapat bahwa dosa adalah kegagalan dari tindakan yang sempurna dan dengan demikian tidak sesuai dengan kemahakuasaan.[5] Teori alternatifPaul Copan berpendapat dari sudut pandang Kristen bahwa manusia, yang diciptakan dari gambaran Tuhan, sehingga manusia juga tunduk dengan moralitas Tuhan. Manusia memiliki deskripsi tindakan yang berstatus benar atau salah karena itu relevan dengan moralitas Tuhan; perasaan seseorang tentang apa yang benar atau salah sesuai dengan perasaan Tuhan.[24]
Sebagai alternatif dari teori perintah ilahi, Linda Zagzebski telah mengajukan teori motivasi ilahi, yang masih sesuai dengan kerangka monoteistik. Menurut teori ini, kebaikan ditentukan oleh tujuan Tuhan, bukan oleh apa yang Dia perintahkan. Teori motivasi ilahi terlihat serupa dengan etika kebajikan karena menganggap agen karakter serta kesesuaiannya dengan tujuan Tuhan sebagai standar nilai moral.[25] Zagzebski berargumen bahwa banyak hal di dunia memiliki sifat moral objektif yang diberikan kepada hal-hal tersebut melalui pengetahuan Tuhan tentang mereka. Sikap Tuhan terhadap sesuatu dianggap sebagai sikap yang baik secara moral.[26] Teori tersebut menjadikan Tuhan sebagai teladan yang baik dalam hal moralitas, dan manusia harus mencontoh kebajikan-Nya sebanyak mungkin karena mereka adalah makhluk yang memiliki keterbatasan dan tidak sempurna.[27] BantahanBantahan semantikFilsuf William Wainwright membuat sebuah tantangan terhadap teori tersebut dengan dasar semantik. Dia berargumen bahwa "diperintahkan oleh Tuhan" dengan "diwajibkan" bukanlah hal yang memiliki arti yang sama, berkebalikan dengan apa yang dikatakan oleh teori perintah ilahi. Dia menggunakan contoh kata "air" yang tidak memiliki arti yang serupa dengan H2O untuk menunjukkan bahwa "diperintahkan oleh Tuhan" tidak memiliki arti yang serupa dengan "wajib". Tantangan ini bukan merupakan sebuah bentuk bantahan terhadap kebenaran teori perintah ilahi, tetapi Wainwright percaya bahwa hal itu menunjukkan bahwa teori tersebut tidak boleh digunakan untuk merumuskan pernyataan tentang arti kewajiban.[28] Wainwright juga mencatat bahwa teori perintah ilahi mungkin menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat mempunyai pengetahuan moral apabila ia mempunyai pengetahuan tentang Tuhan. Edward Wierenga berargumen bahwa jika demikian halnya, maka teori tersebut tampaknya menyangkal pengetahuan moral orang-orang ateis dan agnostik.[29] Hugh Storer Chandler juga memberikan tantangan terhadap teori yang dilandaskan pada ide-ide modal tentang apa yang mungkin ada di dunia yang berbeda. Dia mengatakan bahwa, bahkan jika seseorang menerima bahwa diperintahkan oleh Tuhan dan menjadi benar secara moral adalah dua hal yang sama, mereka mungkin tidak sinonim karena mereka mungkin berbeda di dunia lain yang mungkin.[30] Motivasi moralMichael Austin telah mencatat bahwa teori perintah ilahi dapat dikritik karena mendorong orang untuk bermoral dengan motivasi yang tidak murni. Dia menulis tentang keberatannya tersebut sebab menurutnya, kehidupan moral harus dicari karena nilai dari moralitas itu sendiri, bukan untuk menghindari azab atau menerima pahala. Sistem motivasi hukuman dan penghargaan ini dapat dilihat sebagai sesuatu yang tidak memadai untuk moralitas.[5] Dilema Euthyphro Dilema Euthyphro dikemukakan dalam dialog Plato antara Socrates dan Euthyphro. Dalam adegan tersebut, Socrates dan Euthyphro sedang membahas perihal kesalehan ketika Socrates menghadirkan dilema, yang dapat disampaikan dengan bentuk pertanyaan "Apakah X itu baik karena Tuhan yang memerintahkannya, atau Tuhan memerintahkan X karena pada dasarnya itu baik?"[5]
Dilema Euthyphro dapat menimbulkan reaksi bahwa suatu tindakan itu dianggap baik karena Tuhan memerintahkan tindakan itu, atau bahwa Tuhan memerintahkan suatu tindakan karena tindakan itu memang baik. Jika yang pertama dipilih, maka hal itu akan menghasilkan konsekuensi bahwa apa pun yang Tuhan perintahkan harus baik, bahkan jika dia memerintahkan seseorang untuk sengsara, maka perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan harus dianggap bermoral. Namun apabila yang pilihan terakhir yang dipilih, maka moralitas tidak lagi bergantung pada Tuhan dan mematahkan teori perintah ilahi karena Tuhan tunduk pada moralitas eksternal. Selain itu, jika Tuhan tunduk pada hukum eksternal, maka Tuhan tidak lagi berdaulat atau mahakuasa, yang akan menantang konsepsi ortodoks tentang Tuhan. Pendukung dilema Euthyphro mungkin mengklaim bahwa teori perintah ilahi jelas salah karena salah satu jawaban atas dilema tersebut menantang kemampuan Tuhan untuk menetapkan hukum moral.[5] William dari Ockham menanggapi Dilema Euthyphro dengan "menggigit peluru". Dia berpendapat bahwa, apabila Tuhan memang memerintahkan manusia untuk menjadi kejam, maka itu akan menjadi kewajiban moral. William mengajukan pendapat bahwa satu-satunya batasan untuk apa yang Tuhan dapat mewajibkan adalah prinsip non-kontradiksi.[31] Robert Adams membela pendapat Ockham. Dia mencatat bahwa hal itu hanyalah kemungkinan logis kalau Tuhan akan memerintahkan apa yang kita anggap tidak bermoral, namun bukan dalam kenyataan. Bahkan jika Tuhan secara logis dapat memerintahkan tindakan kejam tersebut, dia tidak akan melakukannya karena itu bukan sifat-Nya.[5] Eleonore Stump dan Norman Kretzmann telah menanggapi dilema Euthyphro dengan mengacu pada doktrin kesederhanaan ilahi, sebuah konsep yang terkait dengan Aquinas dan Aristoteles yang menunjukkan bahwa substansi dan sifat Tuhan merupakan hal yang identik. Mereka mengajukan konsep bahwa Tuhan dan kebaikan adalah hal yang identik dan inilah yang membuat perintah-Nya menjadi baik.[32] Filsuf Amerika William Alston menanggapi dilema Euthyphro dengan mengingat apa artinya bagi Tuhan untuk menjadi baik secara moral. Jika teori perintah ilahi diterima, hal itu menunjukkan bahwa Tuhan itu baik karena dia mematuhi perintahnya sendiri. Alston berpendapat bahwa hal ini bukanlah yang menjadi masalah dan bahwasannya masalah tersebut terletak pada kebaikan Tuhan itu berbeda dari mematuhi kewajiban moral. Dia mengusulkan bahwa kewajiban moral menunjukkan bahwa ada beberapa kemungkinan kalau pelaku mungkin tidak menghormati kewajiban mereka. Alston berpendapat bahwa kemungkinan tersebut tidak ada untuk Tuhan, jadi moralitasnya harus berbeda dari sekadar mematuhi perintahnya sendiri. Alston berpendapat bahwa Tuhan adalah standar moralitas tertinggi dan bertindak sesuai dengan sifat-Nya, yang tentu saja baik. Tidak ada kesewenang-wenangan dalam pendapat ini selain menerima standar moral lain.[5] KemahabaikanGottfried Wilhelm Leibniz, dan beberapa filsuf baru-baru ini, menentang teori tersebut karena tampaknya menyiratkan bahwa kebaikan Tuhan eksis dikarenakan mengikuti perintah-Nya sendiri. Dikatakan bahwa jika teori perintah ilahi diterima, kewajiban Tuhan adalah apa yang dia perintahkan sendiri untuk dilakukan; konsep Tuhan memerintahkan dirinya sendiri dipandang sebagai tidak koheren. Tuhan juga tidak dapat memiliki kebajikan apa pun, karena kebajikan adalah disposisi untuk mengikuti perintah-Nya sendiri, dan jika ia tidak dapat secara logis memerintahkan dirinya sendiri, maka ia tidak dapat secara logis pula memiliki kebajikan apa pun. Edward Wierenga membantahnya dengan mengklaim bahwa apa pun yang Tuhan pilih untuk dilakukan adalah baik, tetapi sifat-Nya berarti bahwa tindakannya akan selalu terpuji. William Wainwright berpendapat bahwa, meskipun Tuhan tidak bertindak karena perintah-Nya, masih logis untuk mengatakan bahwa Tuhan memiliki alasan atas tindakannya. Dia mengusulkan bahwa Tuhan dimotivasi oleh apa yang baik secara moral dan ketika Dia memerintahkan apa yang baik secara moral, itu menjadi kewajiban moral.[5] OtonomiMichael Austin menarik perhatian pada keberatan dari otonomi, yang berpendapat bahwa moralitas membutuhkan agen untuk secara bebas memilih prinsip mana yang mereka jalani. Ini menantang pandangan teori perintah ilahi bahwa kehendak Tuhan menentukan apa yang baik karena manusia tidak otonom, tetapi pengikut hukum moral yang dipaksakan, membuat otonomi tidak sesuai dengan teori perintah ilahi. Robert Adams menentang kritik ini, dengan alasan bahwa manusia masih harus memilih untuk menerima atau menolak perintah Tuhan dan bergantung pada penilaian independen mereka tentang apakah akan mengikutinya atau tidak.[5] PluralismeAustin memandang pandangan bahwa dalam dunia pluralisme agama, tidak mungkin untuk mengetahui perintah Tuhan atau agama mana yang harus diikuti, terutama karena beberapa agama bertentangan dengan yang lain, sehingga tidak mungkin untuk menerima semuanya. Di dalam agama-agama juga terdapat berbagai penafsiran tentang apa yang diperintahkan. Austin mencatat bahwa beberapa tanggapan terhadap keberatan otonomi mungkin relevan, karena seorang agen harus memilih agama dan moralitas mana yang mereka nilai benar. Dia berpendapat bahwa teori perintah ilahi juga konsisten dengan pandangan bahwa kebenaran moral dapat ditemukan di semua agama dan bahwa inspirasi moral dapat ditemukan selain dari agama.[5] Heimir Geirsson dan Margaret Holmgren menentang pandangan bahwa agama yang berbeda dapat mengarah pada Tuhan yang sama karena beberapa agama tidak cocok satu sama lain (agama monoteistik dan politeistik memiliki pandangan yang kontras tentang keilahian, misalnya, dan beberapa dewa Yunani atau Norse yang memperbesar kelemahan manusia). Mereka berpendapat bahwa menentukan tuhan mana yang harus didengarkan tetap menjadi masalah dan bahwa, bahkan dalam suatu agama, pandangan yang bertentangan tentang keadaan Tuhan dan perintah-perintah Tuhan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tampaknya saling bertentangan.[33] Lihat jugaReferensi
Daftar pustaka
Pranala luar
|


