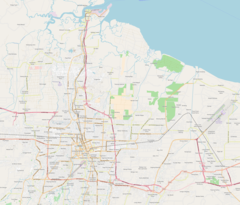|
Kuil Hirohara
Hirohara Jinja (紘原神社, Hirohara Jinja, "Kuil Hirohara") adalah bangunan bekas kuil Shinto di Medan, Sumatera Utara. Kuil ini dibangun pada tahun 1944 oleh Divisi Pengawal ke-2 dari bekas Tentara Kekaisaran Jepang.[3][1] Letaknya berada di belakang Kantor Gubernur Sumatera Utara sekarang. Dari banyaknya kuil Shinto yang dibangun selama pendudukan Jepang di Indonesia, bangunan ini diyakini sebagai satu-satunyayang masih berdiri kokoh dan, kemungkinan besar, merupakan bangunan kuil Shinto terakhir di Asia Tenggara.[4][3] Kuil ini tetap berdiri setelah perang, tetapi sekarang digunakan sebagai tempat pertemuan orang kaya setempat bernama Medan Club. Bangunan ini ditetapkan sebagai situs warisan dan dilindungi oleh Pemerintah Kota Medan.[5] EtimologiNama kuil ini berasal dari dua kata, 'Hiro' dan Hara. 'Hiro' (紘), merujuk pada prinsip 'Hakkō ichiu' (八紘一宇), sedangkan 'Hara' (原) adalah bahasa Jepang untuk 'medan' (lapangan).[1][6] Arti lain dari "Hiro" yakni luas atau ekspansif.[7] SejarahMedan memiliki populasi yang jarang dan tidak mengalami perkembangan yang pesat hingga pertengahan zaman Meiji, ketika penguasa Belanda mulai membebaskan lahan untuk perkebunan tembakau. Pergeseran penggunaan lahan ini memfasilitasi evolusi Medan menjadi pusat perdagangan terkemuka, yang kemudian meningkatkan statusnya menjadi pusat pemerintahan. Tak lama kemudian, berita tentang kemakmuran kota yang berkembang mulai menyebar, menarik gelombang buruh migran, terutama dari komunitas Jepang. Karena itu, Medan menjadi pusat migrasi orang Jepang ke Indonesia di luar Batavia.[8] Laporan konsulat Belanda menunjukkan bahwa ada 782 migran Jepang yang terdaftar di Batavia pada tahun 1909 (dengan perkiraan 400 lainnya yang belum mendaftar), dan tambahan 278 (terdiri dari 57 pria dan 221 wanita) di Medan pada tahun 1910.[9] Penyair terkenal Mitsuharu Kaneko, juga pernah menginap di sebuah penginapan di daerah India di Medan, Kampung Keling, dalam perjalanannya ke Hindia Belanda pada awal zaman Showa. Ia menyatakan bahwa ada lebih dari 40 penginapan yang dikelola oleh Jepang di kota baru tersebut.[10] Para pekerja Jepang kemudian menjadi pengusaha, bahkan beberapa di antaranya menjadi pemilik perkebunan. Menurut cerita penduduk setempat di Medan, sebelum Kuil Hirohara didirikan di lokasi yang sekarang, telah ada sebuah kuil Jepang sebelumnya. Sejarawan, Ichwan Azhari, menjelaskan bahwa karena masuknya para pekerja Jepang ke Medan, yang pada saat itu tercatat mayoritas menganut agama Budha Jepang, maka diperlukan tempat ibadah khusus untuk komunitas yang sedang berkembang.[11] Menurut ketua terakhir Medan Club, Eswin Soekardja, kuil ini dibuat setelah para pekerja Jepang masuk dan menetap di Medan.[12] Invasi Jepang Akira Mutō, Komandan Divisi dari Divisi Pengawal ke-2 merestui proyek ini Setelah Pertempuran Singapura dan Invasi Sumatra, pada tanggal 1 Juni 1943, Divisi Pengawal ke-2 menjadikan daerah Medan di Sumatra, Hindia Belanda (sekarang Indonesia) sebagai basis operasi mereka di Asia Tenggara.[13] Selama perang, kuil-kuil didirikan di seluruh wilayah yang diduduki sebagai tempat berdoa untuk kemenangan dan meningkatkan moral, di Indonesia sendiri terdapat 11 kuil Shinto Jepang.[14] Setelah itu, Mutō kemudian memprakarsai pembangunan kuil miliknya sendiri di atas tanah tersebut.[15] Menurut Prof Nakajima Michio (Mantan Rektor Universitas Kanagawa), bangunan ini dirancang oleh Suzuki Hiroyuki, seorang arsitek dari Kementerian Dalam Negeri Jepang. Pembangunan Kuil Hirohara diperintahkan oleh tentara Jepang, bekerja sama dengan sektor swasta Jepang.[2] Dikatakan bahwa kayu yang digunakan untuk kuil adalah “pohon suci” dari pegunungan Aceh, yang dipasok oleh cabang Showa Rubber di Medan pada masa pendudukan militer, dan bahwa tawanan perang Belanda dan Rōmusha dipekerjakan dalam pembangunannya, sehingga menjadikannya satu-satunya kuil yang dibangun oleh orang Kristen.[16] Salah satu di antara mereka adalah penulis Belanda, Willem Brandt. Dalam karyanya, De gele terreur pada tahun 1946, ia pernah menggambarkan kondisi tersebut:[17][18]
Selama perang, upacara diadakan di Kuil Hirohara pada tanggal 1 dan 15 setiap bulannya, dengan hari ke-8 diperuntukkan bagi Upacara Besar (bahasa Jepang: 大詔奉戴日, diromanisasi: Taishohou Taibi.) Personel militer akan berkunjung untuk berdoa untuk kemenangan, kemudian melakukan Miyagi Yohai (bahasaJepang: 宮城遥拝), sebuah praktik membungkuk ke arah keluarga kekaisaran Jepang (Miyagi) dari kejauhan.[19] Praktik ini tampak aneh bagi penduduk Medan yang sebagian besar beragama Islam, yang bersujud dan solat ke arah Kiblat Ka'bah lima kali sehari. Selama masa pendudukan, beberapa tentara Jepang memaksa penduduk, bahkan orang asing di kamp tawanan perang, untuk menyembah keluarga kekaisaran Jepang dari kejauhan, yang menyebabkan pertentangan karena Miyagi Yohai dilakukan ke arah timur, arah yang berlawanan dengan Mekah di barat.[20][21] Meskipun dasar-dasar agama Islam pada awalnya diajarkan kepada para petinggi pemerintahan militer Jepang yang bertugas di Indonesia, pendidikan ini tidak diterapkan secara menyeluruh, sehingga menimbulkan masalah. Shizuo Saito, mantan duta besar Jepang untuk Indonesia dan Australia[22] dan seorang administrator militer untuk mantan Angkatan Darat Jepang selama perang, menulis dalam bukunya bahwa ia “melembagakan pemotongan rambut” dan “pemaksaan bahasa Jepang”, serta “pemaksaan beribadah dari kejauhan di Miyagi”. Dia menyatakan bahwa penduduk setempat didorong untuk mengunjungi kuil dan dia memaksa mereka untuk beribadah.[23] Meskipun kuil-kuil ini dihancurkan oleh tentara Jepang dan penduduk setempat pada akhir perang, Kuil Hirohara secara misterius tetap utuh. Mengingat terbatasnya pembangunan selama tiga tahun pendudukan Jepang di Indonesia, kuil ini dianggap sebagai struktur sejarah yang signifikan.[24] Medan Club Setelah Jepang menyerah, ada sebuah upaya dilakukan untuk membongkar kuil dari tanggal 26 Agustus hingga 31 Agustus 1945 di bawah perintah Kementerian Dalam Negeri, untuk menghindari penodaan terhadap kuil. Pembongkaran kuil sedang berlangsung dan diawasi oleh Suzuki Hiroyuki sendiri, yang tinggal di Medan selama perang berlangsung.[25] Baik honden dan haiden, serta kuil-kuil kecil lainnya yang ada di situs tersebut, berhasil dibongkar. Proses ini tiba-tiba berakhir ketika pasukan Inggris segera mulai mendarat di Belawan pada tanggal 9 Oktober dan melesat menuju kota Medan,[26] menghadapi sedikit atau bahkan tidak ada perlawanan dan tidak memungkinkan bagi Jepang untuk melakukan tindakan yang menentukan.[27] Akibatnya, sebagian besar infrastruktur dan bangunan di Medan, termasuk shamusho, tetap relatif utuh. Pada tahun berikutnya, Suzuki Hiroyuki kembali ke Jepang.[28] Selama pendudukan kota Medan oleh Sekutu, bangunan ini dialihfungsikan sebagai gedung perkumpulan supremasi kulit putih Belanda yang dikenal dengan nama De Witte Sociëteit.[4][5] De Witte Sociëteit didirikan pada tahun 1879, berfungsi sebagai tempat berkumpulnya orang kulit putih, Belanda Totok, Tionghoa, pemilik tanah berpangkat tinggi di Deli, dan Sultan Deli sendiri;[29] tidak ada orang Inlander dan anjing yang diizinkan masuk.[30] Clubhouse pertama mereka terletak bersebelahan dengan kantor pos utama Medan (sekarang Bank BCA). Club House pada awalnya dirancang sebagai tempat berkumpulnya para pemilik perkebunan Belanda di mana mereka dapat berkumpul untuk melakukan kegiatan rekreasi. Kegiatan ini meliputi menikmati minuman seperti kopi, merokok, dan berpartisipasi dalam diskusi mulai dari sastra dan bisnis hingga politik, seni, dan budaya.[31]  Setelah kepergian Belanda dari Indonesia, mantan anggota militer KNIL, Dr. Hidayat, Dr. Soekarja, Dr. Hariono, dan Dr. Ibrahim Irsan mengambil alih gedung clubhouse ini dan menamainya “Medan Club”. Medan Club adalah tempat eksklusif untuk kalangan atas masyarakat Medan. Keanggotaan diperlukan untuk mengakses fasilitas Medan Club.[32] Yayasan Medan Club, yayasan yang sebelumnya dimiliki oleh 150-200 anggota, yang menjalankan operasi, administrasi, dan pemeliharaan bekas kuil, mengaku mengalami kesulitan keuangan,[33] dengan pemasukan yang hanya diperoleh dari iuran anggota bulanan dan biaya operasional yang tinggi. Hal ini menyebabkan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan sejak tahun 2009, dengan total hutang sebesar Rp.964.154.774, termasuk denda keterlambatan. Dinas Pendapatan Medan telah mengirimkan empat surat tagihan pajak sejak tahun 2013 dan memiliki rencana untuk menerbitkan satu surat tagihan pajak lagi di kemudian hari.[34] Di tengah kesulitan keuangan, pada tahun 2018, pemilik Medan Club membuka Medan Club untuk umum dan mengubah Medan Club dari klub eksklusif untuk anggota menjadi restoran dan tempat pertemuan kelas atas.[35][36] Dengan menggunakan opsi ini, pada tanggal 6 Agustus 2018, sebuah seminar diadakan oleh Konsulat Jenderal Jepang di Medan di Medan Club, yang menghadirkan berbagai pejabat sebagai pembicara untuk memperingati 60 tahun hubungan diplomatik antara Jepang dan Indonesia. Perayaan ini mencakup promosi budaya seperti Shodō, Sadō, Furoshiki Wrapping, serta seni pertunjukan seperti tarian Yosakoi dan karate.[37][38] Setahun kemudian, pemiliknya kemudian berniat untuk mengubah klub ini menjadi klub hiburan 'kehidupan malam'. Perubahan yang tiba-tiba ini menimbulkan pengawasan karena klub Medan belum mendapatkan izin usaha yang diperlukan untuk beroperasi sebagai tempat hiburan malam dan hanya memiliki izin restoran.[39] Di tengah kesulitan keuangan dan tingginya biaya pemeliharaan bangunan kuil, klub ini berada di ambang kebangkrutan. Rencana pembongkaran bekas kuilPada 28 Oktober 2021, bekas kuil tersebut secara resmi ditetapkan sebagai situs cagar budaya oleh Pemerintah Kota Medan. Pengakuan ini didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Pemerintah Kota Medan nomor 433 tahun 2021, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Bobby Nasution.[40] Secara tak terduga pada tanggal 9 Juli, pemerintah provinsi melarang penjualan tanah tersebut kepada pihak ketiga selain pemerintah provinsi sendiri. Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, kemudian mengungkapkan rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membeli Medan Club. Merasa perlu untuk mengembangkan lahan dan memperluas fasilitas perkantoran untuk kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat.[41][42] Meskipun seorang juru bicara secara samar-samar menyatakan bahwa pembelian Medan Club tidak akan serta merta mengakibatkan “hilangnya Medan Club”, dan berniat untuk membeli lahan lain di dekat gedung tersebut untuk menggantikannya.[43] Lahan tersebut disetujui untuk dibeli dengan harga lebih dari Rp457 miliar (atau $28,777,000). miliar (atau $28.567.070,00 dalam USD) dan telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Utara tahun 2022 sebesar Rp.300 miliar dan sisanya sebesar Rp.157 miliar lebih, diperkirakan pada APBD Sumatera Utara 2023.[44] Pembelian ini menuai kritik, mulai dari urgensi untuk kepentingan masyarakat Sumatera Utara, hingga harganya.[45] Edy menanggapi kritik ini dengan mengatakan bahwa seandainya lahan tersebut tidak dibeli, lahan Medan Club dapat dibangun kembali sebagai hotel, apartemen, atau alun-alun. Dia lebih lanjut berpendapat, “Bayangkan sebuah bangunan yang bisa setinggi 50 lantai sementara gedung pemerintah hanya 10 lantai, bayangkan itu."[46][47] Dia juga berencana untuk membeli sebuah rumah tua di samping bekas kuil tersebut.[48] Mekanisme pembelian tersebut juga dikatakan melanggar peraturan karena Kuil tersebut dibangun di atas lahan milik Kesultanan Deli,[49] yang dianggap tidak pernah mendapat ganti rugi. Pemerintah Kelurahan Suka Piring dan pihak-pihak yang mewakili ahli waris Sultan Deli menggugat Pengurus Perhimpunan Medan Club sebesar lebih dari Rp 442,9 miliar di Pengadilan Negeri Medan. Akhmad Syamrah, juru bicara Suka Piring, mengklaim bahwa lahan yang akan digunakan untuk perluasan Kantor Gubernur Sumatera Utara tersebut adalah milik masyarakat adat Deli, karena dulunya lahan tersebut merupakan konsesi dari kesultanan yang diberikan kepada Medan Deli Maatschappij. Berdasarkan UU No. 86 tahun 1958, semua tanah dan bangunan yang dulunya dikuasai dan dioperasikan oleh Belanda kemudian dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia dan dinyatakan sebagai milik negara. Namun tidak diketahui secara pasti apakah pengambilalihan Medan Club dari De Witte Sociëteit merupakan hasil nasionalisasi atau pengambilalihan.[50][51] Seiring berjalannya waktu, masalah ini dianggap sah setelah adanya keputusan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.[52] Pada tanggal 16 Januari 2023, pembatas antara bekas kuil dan kantor provinsi telah dihancurkan,[53] dengan tujuan untuk menggunakan lahan tersebut untuk tempat parkir dan kegiatan sosial setempat untuk sementara waktu.[54][55] Sebagai buntut dari penghancuran pembatas tersebut, legalitas pembongkaran tersebut dipertanyakan, apakah pemerintah provinsi dapat menghancurkan sebuah situs cagar budaya mengingat statusnya sebagai cagar budaya. Isnen Fitri, seorang profesor di Universitas Sumatera Utara, memberikan perspektif netral terhadap pembelian tersebut. Ia percaya bahwa bangunan seperti shamusho dan kota bersifat dinamis dan tidak statis dan dengan demikian, metode seperti mengizinkan perubahan kepemilikan dan fungsi sangat penting untuk mengakomodasi dan memastikan bahwa bangunan bersejarah tetap terlihat saat ini. Meskipun tidak berada pada titik konservasi total atau penghancuran.[56] Ichwan Azhari percaya bahwa Undang-Undang Cagar Budaya dapat dilanggar, namun undang-undang tersebut menyatakan bahwa seseorang tidak diperbolehkan merusak atau mengganti apa pun di dalam bangunan, termasuk bangunan itu sendiri dan lingkungan sekitarnya.[57] Sementara itu, rencana sedang dilakukan untuk membangun sebuah gedung serbaguna di lokasi tersebut, yang berfungsi sebagai pusat layanan publik, perizinan, dan fungsi administratif lainnya. Detail Engineering Design (DED) untuk bangunan tersebut saat ini sedang dipersiapkan, dengan perkiraan anggaran sekitar Rp500 juta. Masa depan bekas kuil ini tidak pasti, dengan kemungkinan pembongkaran total.[58] Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini sedang melobi gedung Partai Perindo, yang terletak tepat di sebelah Medan Club, untuk menjual tanahnya.[59] Karena area termasuk kuil itu sendiri ditetapkan sebagai zona perkantoran dan ketinggian bangunan maksimum untuk area tersebut adalah 13 lantai sesuai dengan Peraturan Daerah Kota No. 2/2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kota Medan 2015-2035.[60][61] StrukturLokasi klub, yang kemungkinan besar mencakup lokasi kuil utama yang lama, memiliki ruangan-ruangan berpartisi bergaya Barat di mana para anggota dapat menyantap makanan lokal dan Barat. Meskipun gerbang torii telah dihilangkan, namun jika diamati dengan seksama, akan terlihat sisa-sisa estetika kuil di masa lalu. Beberapa pohon kuno, yang diyakini sebagai bagian dari lahan kuil asli, masih berdiri di atas lahan tersebut.[62][63] Menurut Eswin Soekardja, lahan yang meliputi bangunan ini dulunya seluas 1,5 hektare (sekarang 1,4 hektare),[64][65] termasuk sebuah lapangan golf yang mungkin dulunya merupakan taman kuil,[66] yang memanjang hingga ke Sungai Deli.[67][68] Shamusho (社務所, kantor kuil), masih tetap sama, meskipun sebagian telah diubah.[69] Terlihat jelas pada lantai kuil, yang sekarang dilapisi keramik dan bukannya panel kayu untuk lantai tanah.[70] Diperkirakan kuil ini tidak memiliki Honden (本殿, aula utama)[71] Meskipun mungkin saja ini adalah fakta bahwa kuil ini telah dihancurkan oleh pembangunan kembali di daerah tersebut. Kuil ini dulunya memiliki Ottori dan kolam di seberang jalan yang sekarang menjadi persimpangan jalan[72] Tujuan utama kuil ini masih belum jelas, karena honden (dan mungkin juga haiden) telah dihancurkan dan hanya sedikit informasi yang ada. Para peneliti dari Universitas Kanagawa yang mengunjungi situs tersebut awalnya berhipotesis bahwa kuil tersebut digunakan untuk menghormati para korban perang, yang dikenal sebagai tipe kuil Gokoku (sebelumnya bernama Shokonsha). Meskipun ada juga yang menduga bahwa honden tersebut mengabadikan Amaterasu Ōmikami, Dewi Matahari dan dewa tertinggi dalam agama Shinto, sehingga menjadikannya sebagai tipe kuil shinmei.[73] Dan bahwa Haiden (拝殿, aula pemujaan) digunakan untuk berdoa bagi kesejahteraan rakyat Jepang dan Indonesia. Meskipun menurut Ito Masatoshi dari Universitas Nihon, kuil-kuil semacam itu tidak dibuat untuk kepentingan dan kesejahteraan penduduk setempat, tetapi lebih karena alasan politik karena berdoa kepada Amaterasu memiliki kedudukan yang sama dengan berdoa kepada Kaisar pada saat itu.[74] Penyair dan penulis Belanda yang terkenal, Rudy Kousbroek, mengunjungi bekas kuil tersebut saat bekerja untuk NRC Handelsblad pada tahun 1980-an. Dia menggambarkan bekas kuil tersebut sebagai “memiliki kecanggihan kesederhanaan, kesederhanaan, dan keheningan. Permukaannya yang tidak dihiasi, proporsi alami, dan kayu mentah membangkitkan estetika yang telah dibudidayakan selama lebih dari seribu tahun, tanpa tampilan kekuasaan, kesombongan, atau vulgar."[75] Kemudian ia menyatakan pada kunjungan pertamanya:[75]
GaleriReferensi
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||